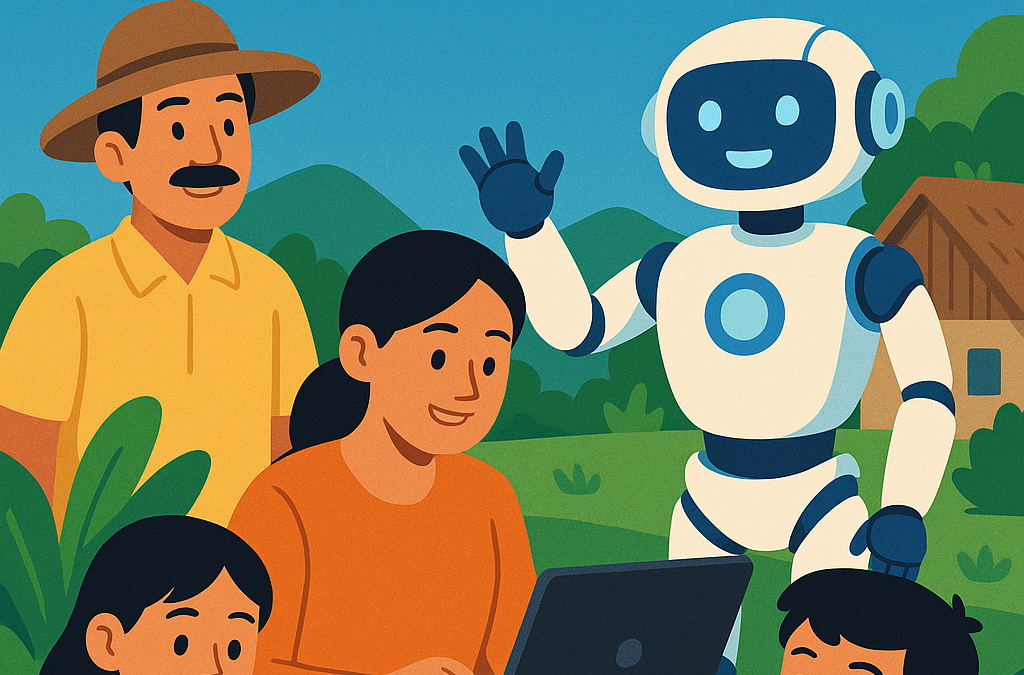SELAMA INI, banyak yang mengira Artificial Intelligence (AI) hanya untuk sekolah di kota besar. Lalu bagaimana sekolah yang ada di pedesaan? Masih identik dengan papan tulis dan laptop lama. Padahal, di era digital, pendidikan dasar tak bisa lepas dari teknologi. Sayangnya, guru di pedesaan masih tertinggal dalam literasi digital dan kemampuan teknologi. AI justru bisa menjadi solusi untuk meringankan beban guru sekaligus membuat belajar lebih menyenangkan bagi siswa.
Melihat kondisi tersebut, sekelompok dosen dari Universitas Nahdlatul Ulama (Unusa) bersama perguruan tinggi lain menginisiasi sebuah program pemberdayaan guru di Kecamatan Yosowilangun, Lumajang. Mereka melatih 20 guru SD agar bisa menggunakan berbagai aplikasi AI dalam mengajar, mulai dari Google AI, Scratch, hingga IBM Watson Tutor.
Selama enam bulan, para guru ini mengikuti workshop, praktik langsung, dan pendampingan rutin. Tidak hanya teori, mereka langsung mencoba membuat rencana pelajaran dengan bantuan AI, menilai tugas secara otomatis, bahkan membuat kuis yang disesuaikan dengan kemampuan tiap murid. Awalnya banyak guru yang merasa ragu karena menganggap AI rumit dan hanya cocok untuk sekolah elit. Namun setelah dibimbing, hasilnya mengejutkan.
Kepercayaan diri guru meningkat pesat, dari rata-rata skor 2,1 sebelum pelatihan menjadi 4,3 setelah pelatihan. Dengan AI, guru juga bisa memantau perkembangan tiap murid secara lebih personal. Misalnya, AI otomatis membuat soal berbeda untuk anak yang kesulitan di matematika, sehingga mereka bisa belajar sesuai kebutuhannya. Tidak hanya itu, data menunjukkan nilai siswa naik hingga 20 persen setelah penggunaan AI, terutama di mata pelajaran sains dan matematika. Guru juga merasa lebih hemat waktu karena pekerjaan administratif, seperti memeriksa kuis, bisa dibantu oleh AI. Dengan begitu, guru memiliki lebih banyak kesempatan untuk fokus mendampingi murid satu per satu. Meski begitu, program ini tentu tidak lepas dari tantangan.
Beberapa sekolah masih terkendala internet lambat dan perangkat yang terbatas. Ada pula guru yang khawatir AI bisa mengurangi interaksi manusiawi dalam kelas. Namun lewat pendampingan dan praktik berulang, perlahan keraguan itu mulai berkurang. Program ini jelas berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Poin keempat, yaitu pendidikan berkualitas, tercermin dari meningkatnya mutu pembelajaran melalui teknologi. Poin kesepuluh, mengurangi kesenjangan, terlihat dari kesempatan anak-anak di desa untuk merasakan pengalaman belajar setara dengan di kota. Sementara poin kesembilan, yakni inovasi dan infrastruktur, terwujud lewat pengenalan teknologi tepat guna di sekolah pedesaan.
Dari pelaksanaan program ini, membuktikan bahwa AI bukan hanya milik kota besar atau sekolah mahal. Dengan pendampingan yang tepat, guru di desa pun bisa menjadi agen perubahan digital, dan anak-anak mereka berhak mendapatkan pengalaman belajar modern yang seru dan bermakna.
Bagi para guru, jangan takut mencoba hal baru. AI tidak hadir untuk menggantikan peran guru, melainkan untuk membantu. Dan bagi pemerintah maupun masyarakat, inilah saatnya memberikan dukungan agar kesenjangan digital tidak semakin lebar. Pada akhirnya, pendidikan berkualitas bukan hanya soal buku dan papan tulis, melainkan tentang memberi kesempatan yang sama bagi setiap anak—di kota maupun di desa—untuk belajar dengan cara terbaik. (Humas UNusa)